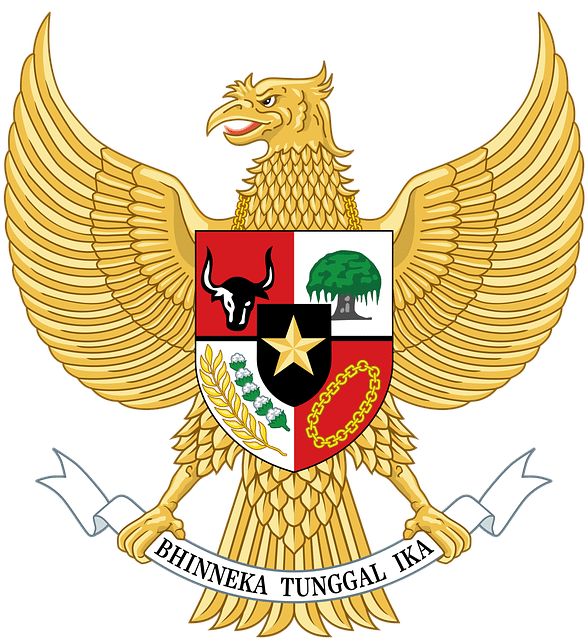Piagam Jakarta 22 Juni 1945 – Munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ke permukaan yang kemudian menimbulkan beragam interpretasi dan respon dari banyak masyarakat, tentu menjadi tanda tanya besar terkait dengan upaya penyadaran dan penguatan pemahaman dan sikap pemerintah orde reformasi serta masyarakat terhadap tatanan kehidupan Pancasila.
Perumusan Pancasila tahun 1945, terdiri dari rangkaian sejarah satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling memberi warna terhadap konsepsi Pancasila. Gagasan the founding father semenjak tanggal 29 Mei s/d 1 Juni, kemudian 22 Juni 1945 seluruhnya adalah “sendi” yang menopang Pancasila.
Dalam tesis Endang Saifuddin Anshari yang diajukannya pada McGill University Canada tahun 1976 dengan judul: The Jakarta Carter of June 1945 : A History of the Gentlemen’s Agreement between the Islamic and the Secular Nationalist in Modern, Indonesia tentu sangat beralasan. Sebab, Piagam Jakarta yang identik dengan frasa “7 kata“ dalam sila pertama merupakan satu fase pembentukan dasar negara yang disepakati oleh pendiri bangsa menjadi gagasan besar untuk membangun Indonesia modern.
Ideologi politik yang terbagi kepada dua kelompok aliran besar; paham kebangsaan dan Islam, yang diperlihatkan oleh arus kecenderungan pemikiran yang berkembang di BPUPK maupun PPKI. Hal ini dengan jelas dikatakan Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945.
Dalam pidatonya tanggal 10 Juli 1945 dalam sidang paripurna Badan Penyidik, setelah Panitia Kecil selesai melaksanakan penyusunan preambule UUD 1945, Soekarno kemudian membacakan hasil rumusan tersebut yang oleh Yamin disebut dengan Piagam Jakarta. Di mana terdapat kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Munculnya frasa 7 kata dalam sila pertama Pancasila, tentu bukan dibuat-buat apalagi disisip tanpa secara sembunyi-sembunyi. Kehadiran 7 kata itu adalah hasil perahan, bukan perasaan oleh panitia sembilan dengan berbagai aliran pikiran yang terdapat di dalamnya. Kelompok mayoritas dan minoritas saling berkesepahaman dengan logika sehat dan kesadaran intelektual yang berwibawa.
Baca juga: Pancasila, antara ‘Weltanschauung’ dan Ideologi
Ada hal menarik dan sangat tepat ungkapan Soekarno dalam pidatonya tanggal 10 Juli tersebut: di dalam preambule itu ternyatalah, seperti yang saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.
Frasa 7 kata dalam sidang panitia kecil yang dipimpin Soekarno memang mengundang perdebatan. Latuharhary seorang Protestan, Agus Salim yang Islam, Wongsonegero, Hoesein Djajadiningrat. Namun Abdul Wahid Hasjim dan Soekarno mengingatkan para peserta sidang, bahwa “anak kalimat itu merupakan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, yang hanya didapat dengan susah payah”.
Dalam penutupan sidang, Soekarno mengulang kembali kata-katanya “oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang menolak, pokok-pokok dalam Preambule dianggap sudah diterima.”
Ketegasan Soekarno juga dipertahankannya ketika persoalan Presiden mesti orang Islam. Logika demokrasi sederhana Soekarno berpihak kepada mengarus utamakan kepentingan mayoritas bangsa Indonesia yang muslim, maka sepantasnyalah presiden itu beragama Islam.
Soekarno dan anggota BPUPK, tidak “lempar batu sembunyi tangan” dalam mengusung dan mempertahankan idenya. Dengan gentleman mereka berargumentasi dan dengan terhormat pula mereka menerima keputusan bersama yang diambil. Soekarno tidak memaksakan kehendaknya. Kehendak bersama dalam pemikiran yang bergemuruhlah maka obor peradaban itu akan hidup dan menerangi.
Peristiwa besar dan cukup monumental dalam sejarah Piagam Jakarta terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pesan penolakan di luar parlemen yang disampaikan kepada Bung Hatta sebagai anggota BPUPK dan PPKI. Isi pesan tersebut terkait dengan kekuatiran kelompok nonmuslim terhadap frasa 7 kata dalam preambule UUD 1945.
Pada tanggal 18 Agustus, sebelum sidang Panitia Persiapan dilaksanakan, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman, Mr. Teuku Hasjim berdiskusi terkait dengan adanya penolakan oleh kelompok nonmuslim terhadap frasa 7 kata tersebut. Ada kalimat penting yang disepakati oleh wakil Islam tersebut yaitu “supaya kita jangan pecah sebagai bangsa”.
Ada pengorbanan luar biasa umat Islam terhadap penghapusan 7 kata tersebut, yang oleh Endang Saifuddin Anshari disebut tidak hanya itu saja, bahkan hampir seluruh klausa “Islami” dalam UUD 1945 juga dihapuskan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan Alamsyah Ratu Prawiranegara “tanpa bantuan dan pengorbanan Islam dan umat Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia”. Pengorbanan umat Islam telah menyatu dalam Pancasila.
Oleh karena itu, adalah langkah yang bijaksana, jika kemudian dalam dekrit 5 Julinya, Soekarno mengatakan “Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD 45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 45, sebagaimana ditulis H. Roeslan Abdulgani.”
Baca juga: Pancasila Jiwa Bangsa
Ada hal menarik dari komitmen politik Soekarno terhadap Piagam Jakarta. Kenapa Soekarno tidak memaksakan jiwa dekrit 5 Juli tersebut kepada Pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa harus kepada Piagam Jakarta, yang di dalamnya jelas-jelas diakui sebagai kesepakatan terbesar bangsa Indonesia dalam menciptakan weltanschauung dan filosofische grondslag.
Sejarah Piagam Jakarta 22 Juni, adalah sejarah politik terbesar bangsa Indonesia dan umat Islam. Islam dan Pancasila tidak bisa dipisahkan, apalagi kemudian dilakukan upaya penghapusan Islam sebagai jiwa Pancasila. Catatan ini penting untuk dikemukakan, agar apa yang terjadi hari ini dengan RUU HIP yang nota bene mencoba menghapuskan Islam sebagai jiwa Pancasila, jelas-jelas adalah tindakan yang melupakan sejarah besar bangsa Indonesia. Pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1966 penting untuk diingat selalu “Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah”.
~ Penulis, Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
~ Gambar oleh ibnuamaru dari Pixabay